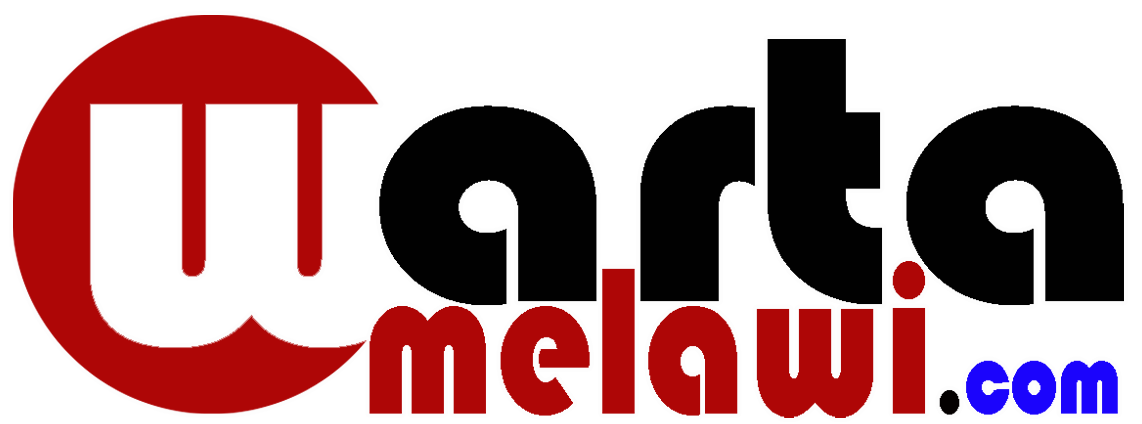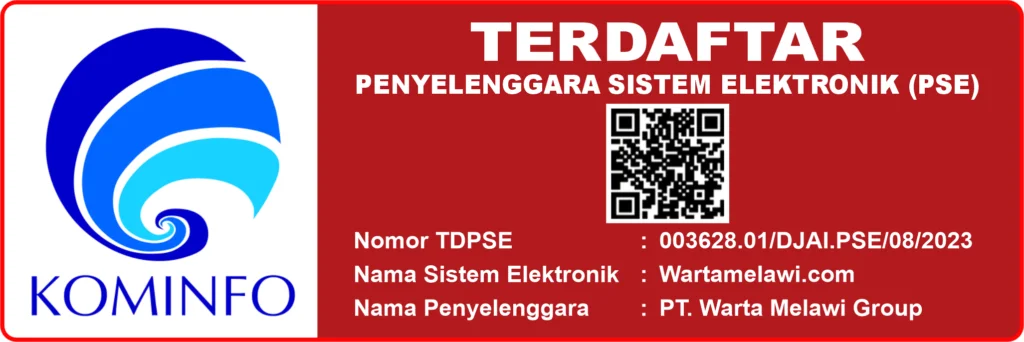Wartamelawi.com – Indonesia kini memiliki lebih dari 229 juta pengguna internet. Platform paling banyak diakses antara lain WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, dan X. Pola pemanfaatannya bervariasi: 24,8% digunakan untuk media sosial, 15% untuk membaca berita online, 15% untuk transaksi keuangan, dan sisanya untuk aktivitas lain.
Laporan Digital News Report 2025 menunjukkan 57% responden di Indonesia memperoleh informasi dari media sosial, bukan lagi dari media arus utama. Artinya, lini masa media sosial telah bergeser dari sekadar ruang percakapan menjadi arena pembentukan opini publik.
Namun, masalah muncul ketika yang viral justru adalah hoaks, miscaption, deepfake, ajakan palsu, atau narasi menyesatkan (logical fallacy). Situasi ini nyata terlihat dalam kerusuhan Agustus lalu.
Data Kementerian Kominfo menyebutkan, sepanjang 2024 terdapat 1.923 konten hoaks yang terdeteksi, sebagian besar bertema politik dan keamanan. Fakta ini menandakan adanya produksi sistematis hoaks oleh individu maupun kelompok, dengan tujuan menciptakan keresahan publik. Budaya “forward” di WhatsApp semakin mempercepat penyebaran.
Empat Ancaman Serius di Media Sosial
- Miscaption
Foto atau video lama diberi keterangan baru. Misalnya, rekaman peristiwa 1998 diedit seolah terjadi pada kerusuhan Agustus 2025. - Deepfake
Rekayasa audio/visual yang meniru tokoh. Contoh: suara buatan AI yang memalsukan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang guru sebagai “beban negara.” Tim MAFINDO telah menguji dan memastikan rekaman itu palsu. - Ajakan Aksi Palsu
Broadcast mengatasnamakan organisasi tertentu untuk mengumpulkan massa, padahal tidak ada agenda resmi. Tujuannya mengarahkan orang ke waktu dan tempat yang salah hingga menimbulkan kerawanan. - Narasi Sesat Pikir (Logical Fallacy)
Biasanya dikemas dalam meme atau flyer. Isinya menyerang pribadi (ad hominem), memutarbalikkan argumen (straw man), mengikuti arus mayoritas (bandwagon), menyudutkan pilihan (false dichotomy), atau menggantungkan kebenaran pada figur otoritas semata (appeal to authority).
Jika keempat jenis konten ini beredar hampir bersamaan, efeknya saling memperkuat: memicu emosi, merusak kepercayaan publik, menggerakkan kerumunan, dan menyesatkan cara berpikir masyarakat.
Peran Pemerintah
Sebagian besar masyarakat tidak memiliki kemampuan memverifikasi konten digital. Karena itu, pemerintah harus hadir. Salah satu langkah strategis adalah membentuk command room satu pintu yang memantau hoaks secara real time, kemudian merespons dalam hitungan menit.
Respons ini perlu disiarkan melalui televisi, radio, media online, hingga platform media sosial. Dalam kondisi genting, konferensi pers berkala menjadi kewajiban agar publik tidak terjebak informasi palsu.
Kecepatan klarifikasi adalah kunci. Riset APJII 2024 mencatat rata-rata warganet Indonesia menghabiskan 3 jam 6 menit per hari di media sosial. Dalam ekosistem digital yang serba cepat, klarifikasi lambat sama artinya memberi ruang bagi hoaks untuk menyebar luas.
Kerusuhan Agustus 2025 menjadi pelajaran nyata: pemerintah harus sigap melakukan debunking, menyajikan bukti terverifikasi, dan menghentikan hoaks sebelum meluas.
Penulis adalah Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Guru Besar Universitas Negeri Makassar, dan Wakil Rektor Universitas Jayabaya Jakarta.
Oleh: Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH